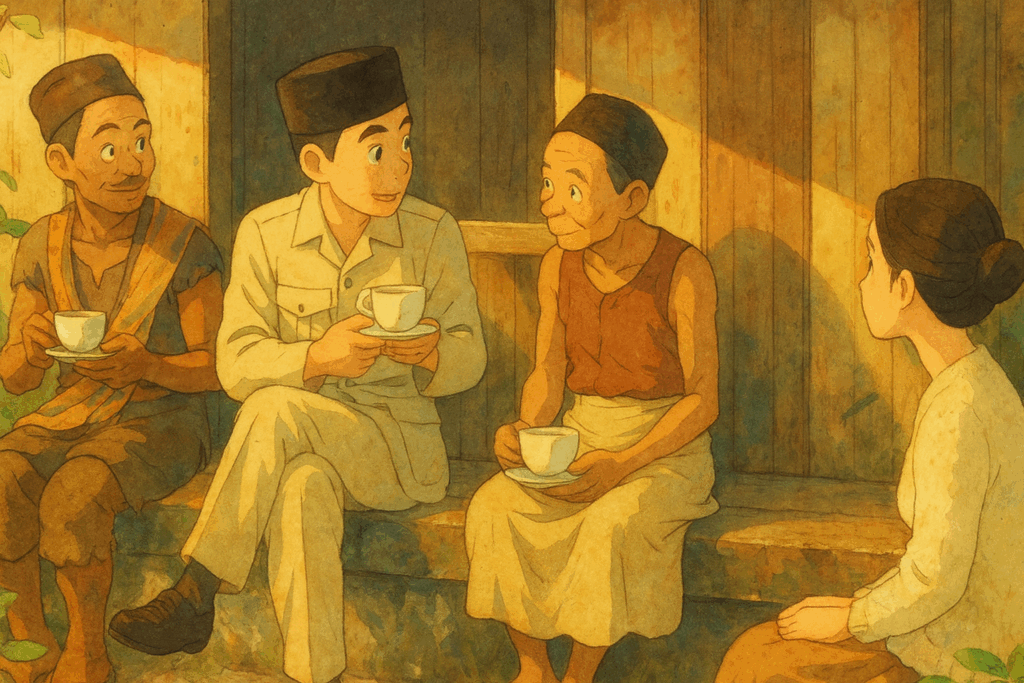Pagi di kota: klakson tipis, driver ojol nunggu orderan, warteg buka lebih dulu dari matahari, dan di layar kita—banjir promo “checkout sekarang!”. Di tengah rutinitas yang kedengaran sangat 2025 itu, nama “Marhaen” dari pidato Soekarno muncul lagi, bukan sebagai nostalgia museum, tapi semacam kacamata untuk melihat siapa yang benar-benar menggerakkan ekonomi… dan siapa yang kebagian remah.
Siapa “Marhaen” Versi Soekarno?
Bung Karno memakai “marhaen” untuk menyebut rakyat kecil yang punya alat produksi—cangkul, perahu, gerobak, kios—namun posisinya tetap ringkih karena struktur ekonomi yang timpang. Mereka bukan buruh pabrik klasik; lebih mirip produsen kecil yang mandiri tapi rawan goyah. Dari situ lahir marhaenisme: kemandirian, gotong royong, anti-eksploitasi, dan emansipasi dari ketergantungan—baik pada modal raksasa maupun imperialisme gaya lama.
Diterjemahkan ke bahasa sekarang: marhaenisme ingin yang kecil naik kelas tanpa melepas kendali atas alatnya sendiri. Sederhana? Nggak juga, tapi masuk akal.
Marhaen Hari Ini: Dari Cangkul ke Dashboard
Lompat ke hari ini. Alat produksi berubah rupa: akun toko di marketplace, motor + aplikasi, kamera ponsel, data pelanggan, rating bintang, bahkan template invoice. Penjual rumahan, desainer lepas, konten kreator, nelayan yang jual via grup WA—alatnya ada di tangan, tetapi pintu pasarnya dijaga algoritma dan biaya layanan. Sekali aturan platform geser, omzet ikut oleng. Sekali ongkir naik, margin langsung kempis.
Apakah ini ketergantungan model baru? Agak, iya. Marhaenisme lalu mengingatkan: kepemilikan alat produksi berarti juga kendali atas akses—atas distribusi, data, dan harga yang fair. Tanpa itu, alat cuma jadi aksesori.
Data: Alat Produksi yang Tak Kelihatan (Tapi Mahal)
Dulu alat produksi bisa dipegang. Sekarang ada satu yang licin: data. Riwayat belanja, pola klik, alamat pengiriman. Nilainya nyata, tapi sering bukan milik produsen kecil. Kalau pelaku UMKM tak bisa mengakses datanya sendiri, susah membangun merek, menawar biaya iklan, atau menjaga pelanggan setia. Kedaulatan ekonomi hari ini—setengahnya terjadi di server. Sedih? Bukan; ini alarm.
UMKM: Ulet, Kreatif, Tapi Kenapa Tetap “Napas Pendek”?
UMKM lincah beradaptasi: live shopping, bundling, kolaborasi lintas kota. Masalahnya, ketahanan mereka sering disangga jam kerja panjang, bukan posisi tawar. Biaya sewa, iklan, fee platform—kalau dijumlah, dompet bisa megap-megap. Di sini marhaenisme terasa praktis sekali: gotong royong sebagai strategi bisnis. Rantai pasok bareng, gudang komunal, pembelian bahan baku kolektif. Kedengarannya remeh, tapi margin bisa pulih pelan-pelan.
Bab Tambahan Zaman Ini: Iklim
Soekarno menekankan anti-imperialisme; zaman kita menambah satu bab besar: krisis iklim. Siapa paling kena banjir, gagal panen, cuaca acak? Ya, marhaen juga. Maka marhaenisme 2.0 perlu transisi hijau yang adil: insentif bagi praktik produksi ramah lingkungan, akses pembiayaan murah untuk teknologi hemat energi, dan pasar yang menghargai keberlanjutan. Bukan greenwashing; green income.
Koperasi, Tapi Digital: Bukan Nostalgia—Model Bisnis
Kata “koperasi” sering bikin ngantuk. Padahal logikanya sangat startup: skala lewat kolaborasi, bagi hasil adil. Bayangkan platform koperasi di mana driver adalah pemilik aplikasinya, pedagang pemilik marketplacenya, kreator pemilik jaringannya. Biaya layanan bisa ditekan, aturan disepakati anggota, data dibagi transparan. Susah? Tentu. Tapi marhaenisme memang bukan jalan tol; lebih mirip gang kampung yang diperlebar bareng-bareng.
Perlindungan Sosial: Ikut Orang, Bukan Ikut Kantor
Kerja sekarang cair: hari ini kurir, besok fotografer, lusa admin medsos. Artinya, jaring pengaman perlu portabel—BPJS/iuran fleksibel, asuransi kecelakaan yang bisa dibawa lintas proyek, pensiun mikro. Kemandirian tak boleh berarti “sendirian”. Ini poin etis sekaligus ekonomis.
Pangan & Tanah: Rumah Lama yang Belum Beres
Soal pangan tetap inti kitab marhaenisme: keadilan agraria, akses benih, diversifikasi komoditas, pasar lokal yang kuat. Ketika rantai pasok global batuk, lumbung pangan komunitas, koperasi tani, dapur umum—semuanya jadi shock absorber. Urban farming oke—asal bukan sekadar estetik feed; harus nyambung ke dapur tetangga.
Literasi Digital: Ngitung yang Nyata
Marhaenisme itu kebiasaan sehari-hari. Literasi digital berarti paham metrik toko, biaya tersembunyi, negosiasi kontrak, hingga jebakan “pay later” yang merusak arus kas. Di tingkat komunitas: kelas foto produk, akuntansi dasar, template kontrak untuk freelancer, dan pengetahuan hukum kerja—yang sederhana tapi bikin berdaya. Teori boleh di kepala, angka tetap di kalkulator.
Nasional Tanpa Paranoid
Bung Karno bicara kedaulatan, bukan anti-dunia. Era open-source dan kolaborasi lintas batas menuntut dua langkah: kuasai teknologi hulu (cloud lokal, AI terapan untuk UMKM, pembayaran murah lintas platform) sekaligus kompetitif di hilir. Nasionalisme yang percaya diri—bukan menutup diri.
Penutup: Dari Slogan ke Kebiasaan
Pada akhirnya, marhaenisme adalah cara menanyai ekonomi: siapa punya alat, siapa pegang pintu, siapa dapat nilai. Di zaman aplikasi, jawabannya gesit berubah—kadang licin. Karena itu kita butuh Marhaenisme 2.0: koperasi digital yang benar-benar hidup, data milik anggota, perlindungan sosial portabel, transisi hijau yang berpihak pada yang kecil, dan literasi digital yang membumi.
Utopia? Mungkin separuh. Separuh lain sangat teknis dan bisa dimulai hari ini: tetapkan standar bayar adil untuk freelancer, bikin kelompok beli bahan baku lintas toko, dorong asosiasi pekerja platform di kota, dan—ini sering yang paling berat—berhenti merasa kecil sendirian. Marhaen, pada akhirnya, itu plural. Ketika kumpul, ia jadi kelas—dan kelas ini punya suara.